Editorial Kumpulan Tulisan: Daur Subur
Ibaraiknyo tanah: nan lereng tanami padi, nan tunggang tanami bambu, nan gurun jadikan parak
nan bancah jadikan sawah, nan padek kaparumahan, nan munggu jadikan pandam, nan gauang ka tabek ikan, nan padang tampek gubalo, nan lacah kubangan kabau, nan rawang ranangan itiak.
(ibaratkan tanah: yang lereng tanami padi, yang curam tanami bambu, yang gurun jadikan ladang, yang menggenang jadikan sawah, yang padat untuk perumahan, yang membukit jadikan perkuburan, yang gauang untuk kolam ikan, yang padang tempat bergembala, yang berlumpur kubangan kerbau, rawa-rawa tempat itik berenang.)
Mamangan di atas adalah ungkapan tentang pemanfaatan lahan secara efesien, menunjukan bahwa dalam kondisi apapun kita diciptakan memiliki potensi dan manfaat masing-masing. Menarik melihat ini sebagai manifestasi orang Minangkabau dulu mengemas data yang tersedia pada alam dan kemudian dikelola kembali secara praktikal maupun sebagai ilmu pengetahuan. Alam adalah data yang menuntut kita membaca kembali apa yang disimpannya. Orang Minangkabau pada ‘masa awal’, sepertinya telah menyadari itu, selain alam sebagai falsafah hidup, memanfaatkan dan mengolah hasil sumber daya alam merupakan profesi utama di Minangkabau. Profesi utama itu semisal bertani, yang kemudian memunculkan profesi-profesi lain untuk mendukung pertanian.
Kebiasaan ini berjalan sudah sekian lama, sehingga ia juga tercermin sebagai unsur-unsur kebudayaan. Kedekatan masyarakat dengan pertanian dapat kita lihat pada bagaimana bahasa, teknologi, pendidikan, kepercayaan, kesenian, pola sosial, dan sistem ekonomi dijalankan. Beragam praktek kebudayaan itu diadopsi dari sifat-sifat alam dan tumbuhan. Barang kali ini bukan sesuatu spesial lagi, banyak pula warga dunia melakukan hal serupa, dengan takaran pemahamannya masing-masing. Tapi yang menarik untuk dibaca kembali adalah bagaimana ia berkembang hingga hari ini di Sumatera Barat.
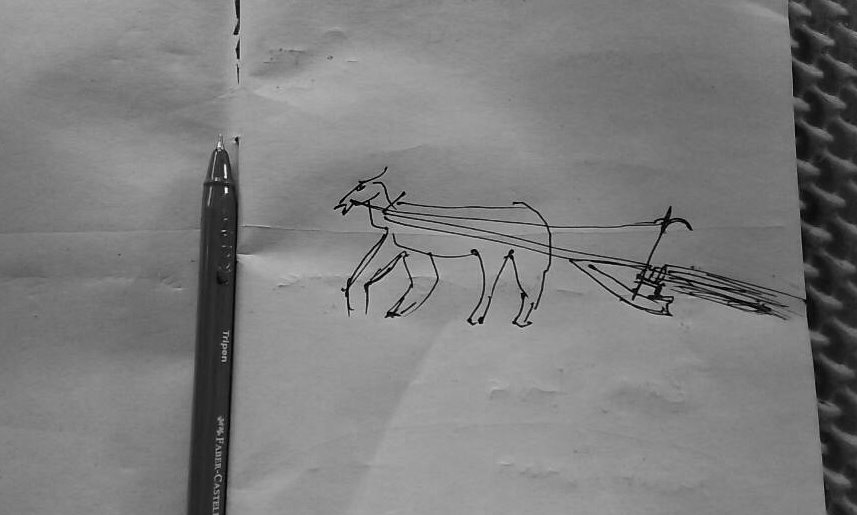
Sejak zaman pra-kolonial, kesuburan alam, kemampuan serta pengetahuan bertani yang sangat baik ini telah tersiar ke berbagai penjuru dunia. Tidak sedikit bangsa-bangsa di dunia ingin menikmati hasil alam Minangkabau, dan tidak sedikit pula memaksa untuk memilikinya. Pola-pola kolonial mulai diterapkan oleh Belanda. Masyarakat kemudian secara paksa harus menanam dalam skala yang besar untuk memenuhi sirkulasi kapital. Pendapatan sering kali tidak sesuai dengan keringat, alam menjadi rusak, seterusnya, ilmu-ilmu alam yang sebelumnya dipelajari pun menjadi tidak seimbang.
Tapi setelah merdeka, seperti pandangan kakek saya, kita sepertinya sudah dibuat canggung oleh lamanya hidup sebagai bangsa yang terjajah. Bahkan beberapa generasi lahir ketika dunia menuntutnya untuk tunduk pada kolonial atau melawan tanpa tahu mengapa. Ilmu-ilmu pertanian secara tidak sadar dikesampingkan. Setelah merdeka kita kembali bangkit dengan segala keterbatasan pengetahuan, menghadapi dunia yang tahu-tahu sudah modern. Dari narasi-narasi yang terkumpul terdengar, di era awal kemerdekaan (dan sedikit sekali saat ini), pengetahuan tentang pertanian itu masih tersimpan di ingatan kolektif warga.
***

Sketsa teknologi pertanian, Daur Subur, Gubuak Kopi, 2017
Sekitar lima tahun lalu, kincir air di kampung saya masih berputar, menyalurkan air sungai ke sawah-sawah warga. Dua tahun kemudian, ia sudah menjadi bangkai, seiiring lahan persawahan berubah menjadi pertambangan emas, dan sungai yang kering. Beberapa petani sebenarnya lebih memilih untuk tetap bersawah, namun sungai tidaklah miliknya sendiri. Kekeringan yang sudah terjadi di hulu, baik itu karena penggerukan emas ataupun sawit tidak bisa ditangkalnya. Akhirnya menyerah juga, tanah dijual pada tambang.
Beberapa waktu lalu dalam diskusi kecil, kita bertanya-tanya. Apa yang akan kita makan 5 tahun lagi. Ada yang memilih mengembangkan pertanian rumahan, salah satunya dengan mengembangkan teknik hidroponik. Hal ini kini mulai banyak kita temukan di lingkungan perkotaan. Lalu apa yang akan terjadi dengan petani kita di perkampungan? Apakah kita akan mengamini ia tereliminasi. Atau mungkin ikut memikirkan caranya untuk sejahtera dan sebagainya. Sebelum berfikiran demikian kita harus terlebih dahulu sadar, petani tidak serta merta pekerjaan ‘tak berdaya’ seperti yang dicitrakan media dan sinetron belakangan ini.
Sejak tahun 70an, pertanian menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Program-program besar untuk petani dirancang sedemikian rupa, hingga kita swasembada dan ekspor. Tapi tidak jarang prakteknya berdampak pada perlakukan petani sebagai alat produksi. Di sisi lain para petani masih saja belum sejahtera dan selalu dianggap sebagai rakyat miskin.
Petani di mata pemerintah sering kali dianggap sebagai objek yang tidak berdaya, yang kemudian harus diberdayakan dengan segala program pemberdayaan. Dalam hal ini petani selalu dianggap sebagai profesi yang tidak perlu mendapatkan pendidikan. Dengan demikian status sosialnya pun diletakan di bawah. Tapi ternyata tidak demikian, dalam lokakarya ini kita belajar banyak dari petani, ataupun dari orang-orang yang mengembangan ilmu alam ini secara organik.
Kembali lagi pada narasi pra-kolonial, alam dan segala tumbuhan adalah data yang jauh sebelumnya sudah dibaca dengan cukup baik oleh orang-orang yang mengelola alam, yang kini kita sebut petani secara general. Dalam pembacaan kali ini kita terkesan mengetahui bagaimana darah sapi dapat mengusir babi, rambut yang dibakar dapat mengusir walang sangit, tentang aroma pupuk kandang yang ternyata mengumpan babi, dan banyak lainnya. Tentang bagaimana kincir dapat berputar secara otomatis, mengairi sawah ataupun menumbuk padi. Tapi memang kemudian kita masuk pada era modern yang turut membuat kita bergantung pada industri pupuk dan pestisida Eropa, atau industri besar di perkotaan. Seperti yang digambarkan tadi pengetahuan lama itu sempat seolah tidak berguna, seiring kerakusan penambang, kerakusan kita membuat lahan seluas-luasnya, penebangan liar, penanaman sawit dan karet dalam skala besar dan sebagainya. Tapi menarik pula mengkritisi diri kita yang tidak berdaya mengatasi persoalan itu, serasa malu menyadari pendahulu kita yang menciptakan alat-alat seperti kincir, yang sangat sederhana sekaligus sangat rumit di masanya.

Pak El, salah seorang pemateri yang kita undang mengisi kuliah di lokakarya ini, menceritakan, dulu biasanya orang-orang yang bertani itu mulai dari yang tidak sekolah hingga tamatan SMP, lalu dibimbing oleh orang-orang tamatan Sekolan Pertanian Menengah Atas (SPMA) langsung di lapangan. Biasanya SPMA tidak dianjurkan untuk kuliah di Unand, karena menurut Pak El waktu itu, biasanya sarjanawan tidak mau turun ke sawah. Maka, biasanya diarahkan untuk melanjutkan sekolah ke akademi pertanian yang belajarnya sekitar satu sampai dua tahun. Tapi memang orang-orang ini selalu turun ke sawah dan membantu petani secara langsung. Tidak jarang pula waktu itu orang-orang dinas selalu berlomba-lomba untuk tampil dan berlumpur di Sawah. Barang kali mereka sangat terkesan dengan gaya foto Suharto yang mengangkat tinggi padi hasil panen. Foto ini kemudian tersebar sebagai poster-poster berkaitan tentang kemakmuran yang didorong oleh negara. Berbeda tipis dengan cara realisme sosialis di Uni Soviet di era Stalin, yang divisualkan dengan kemakmuran petani yang berdaya dan mengangkat sendiri hasil panennya, di saat yang sama anak-anak memberikan bunga pada negarawan dan militernya.
Tapi kini, seperti yang menjadi umpatan petani kebanyakan para terpelajar kita maupun pejabat mempetegas jarak itu dengan menunjuk-nunjuk dari atas pematang. Hal ini kemudian disemarakkan dengan konstruksi yang dibangun oleh media. Bagaimana media arus utama dan sinetron kita secara umum menampilkan para petani sebagai objek untuk dikasihani. Sebaliknya menampilkan kerja-kerja kapital dan bisnis lainnya sebagai pilihan pekerjaan tehormat.
Ketimpangan turut merambat pada kehidupan sehari-hari. Generasi saya atau generasi kini, semua sibuk bercita-cita yang jauh dari apa yang bisa dikembangkan di kampung halaman. SMK sibuk menciptakan mobil, sementara kita juga butuh alat-alat pertanian yang baik sebagai perkembangan terkini di kampung masing-masing. Namun ini sepertinya belum menjadi soal utama, karena spirit survival dan pengetahuan lampau masih bisa kita praktekan sesuai perkembangan sekarang. Kini, di tangan beberapa warga kita bisa temukan styrofoam diolah menjadi lem. Seperti yang dilakukan oleh Buya Khairani, mulut odol bekas pun digunakan untuk penyambung gagang sabit, dan banyak lainnya.
Demikian beberapa gambaran perkembangan lampau dan situasi terkininya bisa diperjelas melalui tulisan-tulisan di buku ini. Selain itu banyak juga praktek terkini yang menarik kita baca dan pahami. Di Kampung Jawa, Kota Solok, kita banyak menemukan rumah-rumah warga dengan taman yang indah dan mengembangkan pertanian ruamahan. Taman-taman tidak hanya diisi bunga-bunga hias, tetapi juga tanaman obat maupun sayuran. Tapi di tempat yang sama kita masih menemukan beberapa ruang terbuka, yang dibiarkan semak dan dipenuhi sampah. Ternyata kesadaran itu tidak bisa kita pukul rata, di beberapa titik menjaga dan merawat lingkungan masih terbatas di ruang privat. Goro-goro yang dicanangkan pemerintah menjadi solusi yang manja setelah kita membaca apa yang baru saja dilakukan warga Gang Rambutan. Tapi di Kampung Jawa juga, satu hingga dua rumah di tepian rel kereta yang sudah semak, warganya berinisiatif untuk membersihkan dan megelolanya menjadi taman. Bermanfaat dan indah dipandang, ketimbang membiarkannya menjadi semak, sarang ular, atau tempat sampah yang tak terkelola.
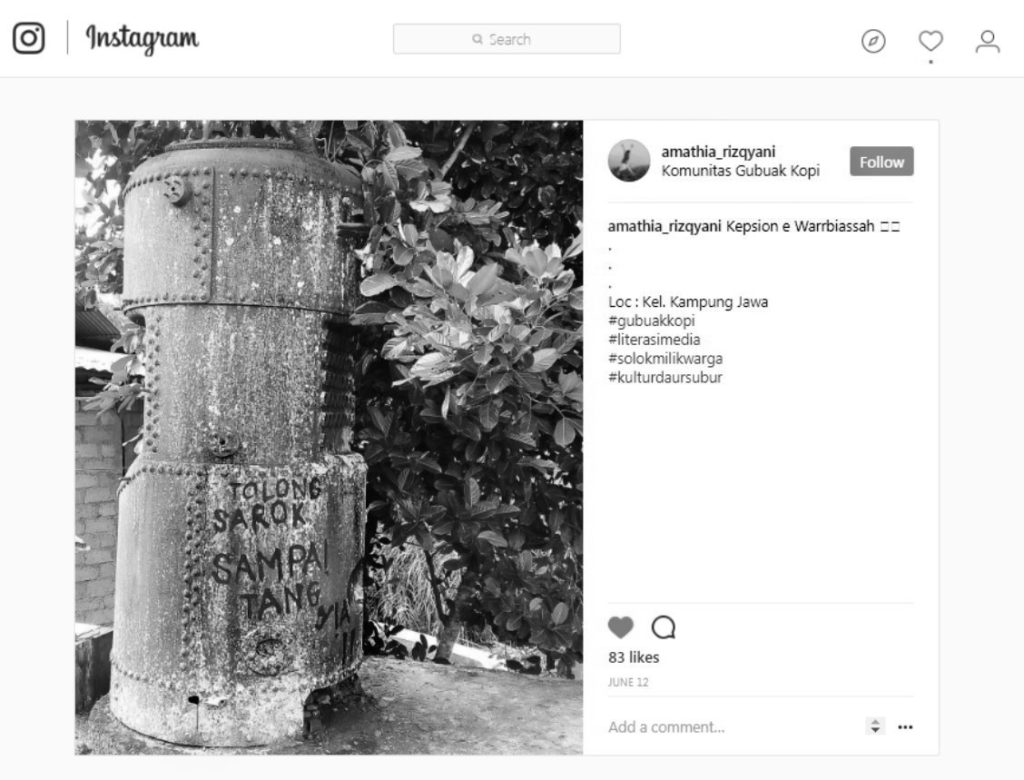
Amathia Rizqyani, salah seorang partisipan lokakarya, ia berjalan ditepian sungai Batang Binguang di Kampung Jawa, menggali kembali ingatannya yang suka mandi di sungai itu sewaktu kecil. Seiring perkembangan zaman dan situasi sosial, sungai yang dulu menjadi kebutuhan, berubah menjadi tempat pembuangan, limbah rumah tangga atau pun sampah lainnya.
Masih di Kampung Jawa, Joe Datuak, partisipan lokakarya lainnya bertemu Da Eng dan beberapa warga lainnya yang berkeliling kampung mencari buah pinang. Ia membeli buah pinang yang tumbuh satu-satu di halaman maupun pembatas taman warga untuk kelola kembali dan dijual. Profesi-profesi yang menarik, yang tumbuh dari situasi pertanian sekarang.
Hari ini kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang segar, yang tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari segala pengetahuan yang telah tersebar dan masih tersimpan dalam ingatan kolektif warga, yang kemudian kita kembangkan di hari ini. Saya tidak menyebutnya karena cerita-cerita lampau, bahwa Eropa yang terkesima dengan cara-cara bertani kita yang sangat maju. Tetapi, tumbuh dengan potensi yang kita miliki rasanya pilihan yang baik. Menarik membaca kembali situasi perkembangan pertanian serta kesadaran lingkungan terkini, melalui praktek media kreatif dan aksi merekam, dengan pendekatan jurnalisme warga dan penelitan sosial. Bersama warga memproduksi pengetahuan bermuatan lokal. ***
Solok, Juli 2017






