Catatan dari pameran “Jajahan Gambar Bergerak” dan Ngobrol Sinema Bersama Kuratornya
Malam itu, 19 Agustus, 2015, kami, para pengunjung, diajak memasuki sebuah ruangan yang gelap. Di dalamnya, beberapa layar bercahaya bergantungan dan menempel di dinding-dinding, membingkai citra diam dan citra bergerak hitam-putih. Di lantai pertama, gambar-gambar yang tersaji merupakan materi arsip terkait sejarah sinema yang didatangkan ke Hindia-Belanda. Arsip-arsip itu dikumpulkan dan dikurasi oleh Mahardika Yudha untuk program Peradapan Sinema dalam Pameran #2 yang bertajuk “Jajahan Gambar Begerak: Antara Fakta dan Fiksi”, bagian dari ARKIPEL Grand Illusion – 3rd Jakarta International Documentary & Experimental Film Festival, yang telah berlangsung dari tanggal 19 – 29 Agustus, 2015. Tajuk tersebut adalah lanjutan dari Peradaban Sinema dalam Pameran #1 di perhelatan ARKIPEL Electoral Risk – 2nd Jakarta International Documentary & Experimental Film Festival tahun lalu, yakni “Jajahan Gambar Bergerak: Lumière (1896-1900)”.
Di lantai pertama itu terpajang beberapa poster dan koran tentang budaya sinema pada awal-awal kedatangannya. Di sana juga terpajang sebuah iklan filem, “Perdjalanan Ka Boelan”, yang mengabarkan bahwa filem itu akan diputarkan di De Royal Bioscope, Manogo Tanah Abang. “Programma baroe sama sekali, keanem kali”, demikian yang tertulis dalam iklan terbitan Pembrita Betawi, 21 Januari 1905 itu.
Pembukaan Peradaban Sinema dalam Pameran #2 malam itu berlangsung di depan Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pameran ini mengajak kita mengenal situasi pada masa awal kedatangan teknologi sinema ke Hindia-Belanda. Dalam sambutannya, Yudha menerangkan bahwa materi-materi yang tersaji dalam ruang yang gelap itu merupakan beberapa arsip sinema tentang kedatangan teknologi perekaman ke Hindia Belanda di rentang periode dari tahun 1896—satu tahun setelah Prancis melakukan pemutaran filem pertama—sampai tahun sebelum masuknya Jepang.
Ketika ditanya mengenai perhelatan tahun lalu, Yudha berkata, bahwa isinya “…tentang beberapa orang Indonesia yang dipamerkan di Inggris, dalam sebuah pameran Kolonial sekitar tahun 1896. Pada waktu itu, beberapa orang Indonesia sedang bermain sepak takraw dan menari pendet, itu di-shoot. Dan buat gue, itulah persentuhan pertama orang Indonesia dengan sinematografi.”
Kemudian, pasca-Lumiere adalah masa ekspansi besar-besaran di dunia, termasuk di Indonesia. Setelah melakukan riset lebih jauh, Yudha berpendapat bahwa ternyata kedatangan sinema di Indonesia itu bukan pada tahun 1900 sebagaimana yang dinyatakan oleh Misbach. Riset kurator yang juga menjabat Direktur OK. Video – Indonesia Media Arts Festival ini menunjukan bahwa sinema sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1896. Setelah diusut, alasan Misbach menyebut tahun 1900 adalah karena pada tahun itulah hadirnya bioskop: Royal Bioscope.
“Bicara tentang bioskop, itu berkaitan dengan industri,” kata Yudha. “Kalau Misbach meletakkan itu sebagai sejarah pertama, bahwa filem adalah industri, gue gak setuju.”
Pada tahun 1896, filem sudah diputarkan secara berkeliling, seperti menggunakan layar tancap. Sajian filemnya pun berfarian, ada filem sirkus, dokumenter, dan fiksi. Filem yang ditayangkan itu pun tidak seperti yang dikatakan oleh Misbach, bahwa kehadiran sinema yang berkaitan dengan bioskop itu juga berkaitan dengan kolonialisasi, contohnya filem tentang Ratu Belanda, yang diputar pada tahun 1900.
“Kalau kita balik ke 1896, itu ternyata nggak cuma ngomongin negara dan semacamnya, tetapi juga ada footage–footage keseharian,” ujar Diki, sapaan akrab sang kurator pameran.
Hal menarik lainnya bisa kita lihat di lantai dua ruang pameran tersebut. Suasana yang tersaji sebenarnya merepresentasikan periode produksi filem pada masa itu.
“Selalu dibilang produksi filem pertama di Indonesia itu Loetoeng Kasaroeng. Dan itu, memang, berkaitan dengan bioskop lagi. Padahal, pada tahun 1906 itu, sudah ada footage–footage tentang Bogor, Jakarta, dan ini mengubah perspektif, ketika yang dianggap sejarah hanya budaya industri (filem bioskop), sedangkan budaya layar tancap dianggap budaya pinggiran.”
Hal itu pun berkaitan dengan fakta bahwa pada saat ini, di era kontemporer, kita menemukan lagi beragam kultur sinema, seperti pemutran keliling, nonton bareng di lapangan, dan gaya pemutaran lainnya yang tidak hanya dilakukan di bioskop—yang belakangan sering diinisasi oleh komunitas-komunitas yang memiliki minat dan ketertarikan dengan dunia filem.
Di lantai dua itu, tiga layar digantung di tengah ruangan, seperti halnya pemutaran pada masa dulu: layar diletakan di tengah lapangan, orang Belanda atau orang-orang kelas atas menonton di depan, sedangkan orang melayu atau orang kelas bawah menonton di belakang, sehingga setiap tulisan dan gambar yang akan dilihat penonton kelas bawah tampil secara terbalik di layar yang mereka saksikan.
Filem yang ditayangkan di lantai dua itu adalah kompilasi dari beberapa filem yang diproduksi di Hindia-Belanda sejak tahun 1905. Salah satu yang saya simak adalah sebuah filem yang bercerita tentang seorang pembantu perempuan dari seorang nyonya Belanda. Mina adalah filem fiksi pertama di Indonesia yang diproduksi 12 tahun sebelum Loetoeng Kasaroeng. Ia sebenarnya, dalam sejarah filem, tidak dianggap filem karena berdurasi pendek. Mina, si pembantu, meminta uang kepada majikannya, lalu si pembantu mengambil sisanya. Kemudian, di sela tugasnya, sebalik dari pasar, si pembantu bermesraan terlebih dahulu dengan pacarnya di sebuah taman.
“Persis seperti yang masih banyak kita temukan di sinetron zaman sekarang. Ini adalah salah satu contoh dari migrasi yang terjadi, migrasi perspektif. Prespektif seperti filem Mina itu sudah dibangun sejak zaman belanda. Dan buat gue, itu dosa-dosa filem,” Yudha melanjutkan.
Pada pameran ini, Yudha mengkurasi arsip-arsip itu dengan fokus kerangka berpikir mengenai masuknya teknologi sinema ke Indonesia. Yudha menilai peristiwa kehadiran sinema ke Indonesia sebagai semacam migrasi pengetahuan, sudut pandang, dan ilusi-ilusi yang dihadirkan melalui teknologi sinema dari negeri-negeri Eropa ke Hindia-Belanda. Filem-filem tersebut dikonsumsi dan diapresiasi oleh masyarakat Hindia-Belanda. Keberadaan sinema-sinema ini jugalah yang sekaligus memengaruhi perkembangan estetika sinema tanah air pada masa-masa berikutnya.
Untuk program Peradapan Sinema Dalam Pameran tahun depan, Yudha berencana akan tetap mencoba menghadrikan kelanjutan Sejarah Sinema di Indonesia itu secara runut.
“Gue pengennya, sih runut, masih tentang sejarah sinema Indonesia,” akunya. “Tapi itu juga tergantung dengan tema ARKIPEL. Mungkin bisa tentang sinema pada zaman Jepang, atau sinema oleh orang-orang Tionghoa.”
Konsep ‘jajahan’ yang saya tangkap dari pameran itu, salah satunya, adalah bagaimana pemerintahan kolonial pada masa Hindia-Belanda yang sangat memegang kontrol produksi dan distribusi filem, membentuk sudut pandang publik mengenai apa yang terjadi pada masa itu. Melalui kekuatan sinema, fakta dan fiksi menjadi sesuatu yang sulit dibedakan, menjadi sesuatu yang kabur. Kadang, beberapa aspek sangat berbeda dengan yang diceritakan oleh kakek-nenek kita. Kadang, kehadiran filem-filem ini malah memperlihatkan situasi masyarakat lokal yang akrab dan terlihat baik-baik saja dengan orang-orang Belanda. Persoalan ini, menurut saya, sangat berkatian dengan gagasan dan isu-isu yang biasanya diangkat oleh akumassa. Kehadiran footage tersebut pada dasarnya juga merupakan sebuah referensi mengenai keterlibatan massa dan media pada zaman itu.
“Yang gue pengen, lu lacak gimana aja, tuh, kejadiannya. Karena, sejarah filem dalam periode kolonial, adalah priode yang sangat buram. Kita belum bahas soal filem-filemnya orang Tionghoa. bagi Misbach filem-filem mereka komersial doang, gak ada seninya. Tapi, kalau sekarang, buat gue nggak begitu juga, tapi harus dilihat lagi…” kata Diki, berpendapat.
Dalam hal ini, akumassa selalu menarik sejarah, bagiamana relevansi narasi-narasi itu dengan konteks masa kini. Persoalan menarik bisa muncul dengan pertanyaan sederhana: “Ini, orang-orang yang ada di dalam filem ini, masih ada nggak, ya?”; “Pemutarannya di kota mana aja, ya?”. Sebagaimana yang sedikit dijabarkan oleh Diki, sementara target pemutaran oleh perusahan filem pada masa itu adalah di kota urban, filem-filem propaganda biasanya justru menyasar desa-desa, seperti persebaran filem-filem yang dibawa dari Eropa. Seperti filem tentang Ratu Belanda dan filem tentang perang antara Belanda dan Inggris. Filem-filem ini dengan sengaja membangun citraan Belanda yang perkasa.
Sejalan dengan tema kurasi pameran, ARKIPEL 2015 mengusung tema Grand Illusion. Sebuah judul filem produksi tahun 1937 karya salah satu master sinema dunia, Jean Renoir. Ide filem ini berangkat dari buku The Great Illusion, A Study of the Relation of Military Power to National Advantage karya Norman Angell tahun 1910 yang bercerita tentang kritik kemanusian, yang disebut-sebut memiliki kaitan denga peristiwa Perang Dunia I yang terjadi setelah buku itu terbit. Hafiz Rancajale, dalam kata pengantar artistik festival, menyebutkan bahwa gagasan Renoir dan Angell adalah melihat bagaimana persoalan kemanusiaan dalam peradaban kita telah tercerai berai oleh konflik dan pilihan-pilihan politik.
Tema Grand Illusion tersebut, seperti penjelasan Yuki Aditya, Direktur Festival ARKIPEL, yang telah dimuat di situs resmi ARKIPEL (www.arkipel.org), relevan dengan situasi politik dan perubahan demokrasi Indonesia yang mulai menuju arah perbaikan dalam situasi politik internasional yang begitu dinamis, namun di sisi yang lain persoalan kemanusiaan masih tetap menghantui bangsa ini. Begitu juga terjadi pada bangsa-bangsa lain, di mana persoalan kemanusiaan merupakan luka yang perlu disembuhkan. Sejarah kemanusiaan masih banyak yang sangat gelap, karena dikaburkan untuk melanggengkan atau melindungi kelompok tertentu.
Mahardika Yudha memilih untuk menjabarkan gagasan tema itu dalam bentuk pameran sinema. Seperti yang kita ketahui semua, saat ini kultur menonton filem tidak lagi hanya dengan membelakangi proyektor. Sekarang kita bisa menonton filem secara bersamaan di tempat yang berbeda, secara online. Misalnya, saat menonton di YouTube, setiap orang di berbagai daerah di dunia ini bisa jadi sedang menonton audio-visual yang sama di situs web yang sama, di rumah atau di mana pun keberadaannya. Tidak seperti dulu saat kita datang beramai-ramai ke bioskop. Jadi, ada beberapa kultur-kultur baru, dan ARKIPEL juga membuka peluang itu. Termasuk juga konsep pameran ini, yaitu bagaimana kita menonton filem itu tidak lagi secara konvensional, seperti hanya duduk di dalam bioskop. Saat menghadiri pameran sinema, penonton harus menonton dengan berdiri, kadang berjalan-jalan, bisa jadi terganggu oleh lalu-lalang pengunjung lain, dan belum tentu berdiam di satu tempat, di hadapan sebuah karya, dalam waktu yang lama.
“Tapi, pada dasarnya, alurnya sama aja dengan alur sinema. Ada pembuka, ada penutup. Klimaksnya di tengah-tengah. Ketika buka pintu (pintu ruang pameran—red), lu berhadapan dengan poster Java Biorama. Kata-kata ‘Java’, buat gue, itu semacam unsur di mana lu melokalkan teknologi asing. Mesin itu sebenarnya disebut biograph, tapi pada masa itu orang-orang menyebutnya dengan Java Biorama. Dan itu diputar di Binjai, bukan di Jawa. Kemudian lu bisa menyaksikan awal kedatangan sinema di lantai satu, dan priode produksinya di lantai dua,” kata sang kurator, menerangkan.
Malam itu, di ruang gelap, layar-layar yang bergantungan menghadirkan gambar-gambar yang buram, diam ataupun bergerak, hitam-putih. Referensi masa lampau yang masih berada di ambang kejelasan antar fakta dan fiksi. Tapi itu bukanlah pokoknya, sebab sinema selalu mengundang kita untuk menfasir lagi dan lagi, menuntut kita memperlakukan daftar-daftar referensi yang buram itu dengan sudut pandang yang baru.


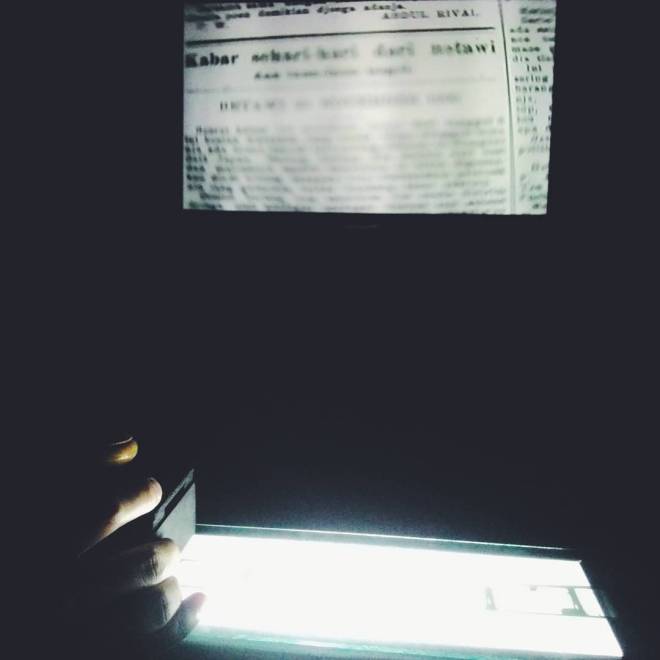

Artikelnya sangat menarik. Maksudnya dari artikel referensi yang buram?